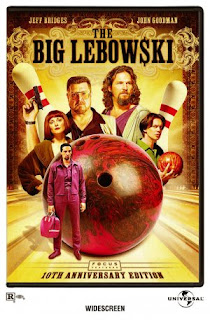Movie Review
SHAME (2011)
“Pertarungan Batin antara Manisnya Kenikmatan Dosa dan Rasa Bersalah
yang Menghantui”
B
|
Didera kontroversi, Shame
menanggung beban berat ketika diluncurkan dengan license tag kuning bertanda seru dari MPAA: NC-17 (No One 17 and
Under Admitted). Lebih buruk dari “sekedar” disegel dengan label “R”
(Restricted). Itu bukti bahwa film ini sangat jelas bukan konsumsi mereka yang
belum dikategorikan sebagai “dewasa”. Sensual. Erotis. Liar. Cabul. Atau
terserah apa sajalah hinaan/pujian yang dapat orang lontarkan terhadap film ini
– tapi Steve McQueen tidak peduli. Dia
dengan semangat idealisnya terus maju dan berjuang meloloskan karya pentingnya
ini dengan cara apapun juga. Tanpa ambil pusing dengan keputusan ketat MPAA dan
kekolotan Oscar, McQueen mempersembahkan kepada anda sebuah film yang akan membuat
jantung berdenyut kencang, nafas terengah-engah, tapi yang paling buruk: emosi
teraduk-aduk tak karuan.
Apa yang lebih buruk dari menjadi seorang sex addict? Sepertinya tidak ada.
Michael Fassbender yang memiliki ketampanan khas British gentleman itu[1]
(dia terliat jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya) memastikan bahwa terperangkap
dalam lingkaran perbudakan seks yang tak terkendali adalah state of nature terburuk yang dapat terjadi pada manusia. Anda
mungkin terliat baik-baik saja di luar, tapi di dalam anda tergerogoti oleh
manisnya racun pengemulsi kesadaran untuk dapat memilih antara yang baik dan
yang buruk. Sebagai Brandon Sullivan, Fassbender mengajak anda masuk ke dalam
kisah yang mengetengahkan seks bukan sebagai sebuah cerita syur yang
mengasyikkan, tetapi sebuah kekuatan mistis yang menyeret dan menenggelamkan ke
dalam lautan kehampaan tak bertepi. Di titik ini, anda akan dapat menyimpulkan
bahwa McQueen berhasil menyajikan ketelanjangan manusia bukan sebagai pornografi,
melainkan sebentuk raga tanpa jiwa.
Tapi di sini Brandon tak sendiri, datanglah Sissy (Carey
Mulligan) adik perempuannya yang manis tapi lancang, suka mencuri-curi tau
dengan apa yang dikerjakannya – termasuk area-area yang terbilang sensitif dan
pribadi. Pun tak ubahnya seperti Brandon, dia memiliki masalah dengan dirinya
sendiri. Cukup satu momen erotika antara dia dan atasan abangnya sudah menjadi
bukti kuat bahwa gadis itu juga kerap terlibat dalam “hubungan-hubungan”
didasari atas desakan nafsu yang sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai “hubungan-hubungan”
yang dilandasi oleh cinta. Beralih dari pelukan satu cinta semalam ke cinta
semalam lain telah menyebabkan jiwa gadis ini rusak. Di kota megapolitan
sebesar New York, one night stand secara
sosiologis barangkali telah menjadi kewajaran sebagai rupa-rupa “sosialisasi” bagi
mereka usia 17 tahun ke atas yang dinyatakan aktif secara seksual di tengah
kemajemukan individu yang secara kolektif kemudian membentuk
komunitas/masyarakat yang dibangun di atas pondasi hubungan inter-personal yang
diukur tidak hanya secara “kuantitas” tapi juga “kualitas”. Tapi melalui studi
karakter terhadap Brandon dan Sissy yang dibeberkan di sini, komplikasi asmara
sesaat tanpa ikatan itu agaknya – dalam jangka panjang – akan menimbulkan
pengaruh psikologis buruk: memperkeruh batas kewenangan yang jelas antara “kesenangan”
dan “kebahagiaan”. Kita tak bisa lagi membedakan apakah seks itu sebatas urusan
“kesenangan” atau lebih dalam berorientasi pada “kebahagiaan”. Secara rasional
anda mungkin mengerti perbedaan maknawiah antara keduanya, tapi tidak ketika
hal tersebut dibuktikan secara empiris. Memang, ini adalah sebuah demokrasi,
tidak semua orang harus sependapat dan ada begitu banyak pendekatan yang patut
diujikan terlebih dahulu berkenaan dengan teori-teori seputar seks tapi secara
lisan dan jujur: apa “standar seks yang baku” menurut anda? Mengakui seks
sebagai “kewajiban alam” atau seks sebagai “pilihan sadar”? Definisikan ulang
arti “kesenangan” dan “kebahagiaan” sebelum anda berani mencampuradukkannya
dengan embel-embel semenggoda, sebombastis, semahal S-E-K-S.
Jangan salah sangka, retorika sinis ini tidaklah sesederhana
itu – tidak dengan mudah dapat “dijawab” hanya dalam waktu sehari saja. Wanti-wanti
saya ingatkan, selama proses perenungan panjang ini, mungkin anda akan
merasakan kegersangan yang sama seperti penderitaan seksual yang digambarkan
begitu dahsyat dalam film ini. Namun, syukurlah, ternyata anda dan saya tidak
sendiri. Kesengsaraan ini juga telah menghajar sang pejantan kita sepanjang
film bergulir. Melalui informasi yang disajiikan dalam bentuk potongan-potongan
gambar cantik oleh McQueen – sebagai karakter yang mewakili bagaimana normalnya
situasi seorang pria lajang dewasa yang keseharian wajarnya menumpuk konsumsi
nutrisi dalam tubuh membentuk hormon yang terus berproduksi tanpa kendali
kemudian menuntut pelepasan hingga pada akhirnya yang terjadi adalah kelaparan,
kerakusan seksual dari seonggok utuh daging dan tulang fana yang hidup namun
perlahan-lahan terenggut visi hakikinya sebagai representasi agung mahluk
berdaya pikir akan makna dan harapan hidupnya – Brandon berupaya keras “menemukan
kebahagiaan” (baca: ketersiksaan) lewat sebuah cara yang mungkin akan anda definisikan
sebagai… saru (kesasar + keliru).
Tak pelak, film memang sebuah media universal yang mampu
menghubungkan emosi dan pemahaman penonton dari belahan bumi manapun – tapi
saran saya, luangkanlah waktu khusus dan tontonlah film ini sendiri, maka film
ini akan terasa begitu personal, lambat-laun “mengganggu”, lantas menampar keras
kesadaran kita akan rahasia tergelap manusia yang kerap disembunyikan, disangkal,
ditutup-tutupi: seksualitas. Membedah fungsi kelamin sebagai organ reproduksi,
McQueen secara efektif menggunakan Shame
sebagai pisau bermata dua – tak hanya mengajukan pertanyaan getir bagaimana
seks menjadi sebuah dorongan psikis yang secara sadar diingini tetapi juga
kebutuhan biologis sebagaimana digariskan oleh hukum alam yang mau tak mau
diikuti – begitu dalam menusuk, merasuk, kemudian menyeruak dan mengobrak-abrik
emosi yang terperangkap dalam sebentuk “kegilaan” (baca: kegelisahan) sukma
akan pelampiasan badani di hadapan sebuah suara kecil yang jujur namun sanggup
meruntuhkan benteng keangkuhan jiwa yang disebut nurani. Namun, jangan harapkan
pesan moral yang memvonis blak-blakan di sini. Tidak. Tidak ada pembicaraan
tentang salah atau benar. Dosa atau suci. Sama sekali tidak ada. Persepsi kolot
one-dimensional yang mentah-mentah
menghakimi semacam itu dengan tegas
dihindari McQueen. Tapi apakah film ini lantas “bablas” tanpa rem? Jelas tidak.
Shame jelas-jelas film yang kejam –
gambaran yang nyaris mendekati fakta tentang ketidaknyamanan yang dirasakan
ketika seks berubah fungsi dari perayaan libido yang indah menjadi teror
kecanduan akut: porsi seks yang korup memukul pertahanan batin, merontokkan
akal sehat, menciptakan horor rasa bersalah berkepanjangan. Terombang-ambing
oleh kemarahan dan keputusasaan – dihantui petualangan seks yang liar, masturbasi,
sex live-streaming, sekardus besar
koleksi pernak-pernik porno –Brandon pada klimaksnya “meledak” dengan rasa muak
yang teramat sangat pada diri sendiri. Lalu, tidakkah dengan begini, akhirnya
McQueen berhasil mengubah persepsi kita bahwa seks tenyata bisa berubah menjadi
sebuah hukuman kejiwaan yang menakutkan?
Michael Fassbender, aktor “pendatang baru” yang namanya
mulai ramai dibicarakan setelah “debut” mengesankannya dalam 300 (2006), Inglorious Basterds (2009), dan terutama Hunger (2008). Sepanjang taun 2011 kemarin, Fassbender menjadi salah
satu wajah yang paling sering muncul dengan tak kurang dari 5 judul film rilis
turut melibatkan namanya: Jane Eyre, X-Men: First Class, A Dangerous Method, Haywire,
dan tentu saja Shame. Penuh
penghayatan menghidupkan karakter Brandon yang mampu membangkitkan mimpi buruk
penonton akan betapa dekatnya keseharian kita dengan seks yang berada di
perbatasan antara kebutuhan dan obsesi – seharusnya Fassbender tak sekedar
meraih pujian dari berbagai kritikus Inggris dan Eropa, tapi patut menembus
nominasi “Best Actor” pertamanya pada penghargaan Oscar kemarin tapi apa yang
terjadi? Bertandang ke Negeri Obama, meski di depan pintu anda disambut hangat,
namun itu sama sekali tidak menjamin bahwa anda telah sukses menaklukkan hati sang tuan rumah. Hanya gara-gara
“nila setitik”, Academy Awards bisa menunjukkan pada anda sikap aristokratis
yang dingin dan acuh. Lagi-lagi AMPAS memainkan peran orangtua “pilih kasih” sehingga
menyebabkan anak seberbakat Fassbender lantas menjadi “tumbal” keangkuhan
mereka. Barangkali mereka pikir ini belum saatnya bagi Fassbender tapi semoga
saja nasib aktor muda tersebut di kemudian hari tidak senaas Gary Oldman yang ironisnya
baru menerima nominasi Oscar perdananya kemarin setelah berkarya di dunia
perfilman lebih dari dua dekade silam. (Bagaimanapun) kudos bagi Fassbender
yang ke depan tampaknya akan menjadi ancaman serius bagi Christian Bale setelah
sukses bermetamorfosis dari pria ceking dalam Hunger menyaingi tubuh kurus kering Bale dalam The Machinist (2004) lalu kini dalam Shame menjelma menjadi predator seks merivalri keberanian Bale berbugil
ria dalam American Psycho (2000). Carey
Mulligan pun ternyata tak sepolos senyum manisnya. Menyusul “saudari
Bennett”-nya dari Pride and Prejudice
(2005), Keira Knightley, dia berani menjawab tantangan untuk melepaskan imej
“gadis baik-baik” yang selama ini membebaninya. Meski porsi penampilannya tak “semelelahkan”
Fassbender, tapi sebagai pemain
pendukung, Mullligan menyuguhkan performa menawan melalui karakter Sissy yang retak,
gamang, kehilangan pemaknaan apresiatif atas diri sendiri, dengan masa bodoh
melanggar etika atas batasan status profesional antara kolega dan abangnya yang
justru semakin memperterang jejak abu-abu hubungan antara “kakak-beradik” ini –
sesingkat momen-momen “kaku” dan dialog “ngawur” yang tertangkap di antara
keduanya – perlahan menyingkap “sesuatu” yang tidak dibahas lebih lanjut oleh
McQueen: misteri masa lalu yang samar-samar mengarahkan penonton untuk
menyimpulkan adanya dugaan (semengerikan) incest.
Sebuah keberanian besar yang patut dipuji ketika sutradara asal
Inggris yang terbilang pemain baru namun memiliki bakat luar biasa, Steve
McQueen (bukan aktor legendaris Hollywood itu) berangkat dari gerakan
perjuangan kolektif dalam Hunger kemudian
lebih intim mempersempitnya menjadi gejolak pergumulan individu dalam Shame. Dalam men-shoot gambar, McQueen juga menyukai detail untuk menegaskan
kekuatan “naratif” film yang tidak melulu harus didominasi dialog
berpanjang-panjang. Melalui kekuatan obyek yang “berbicara” seperti dinding
kaca, lorong apartemen yang lengang, sudut ruangan minimalis, seprai kusut, sejumlah
orang berkumpul di satu sudut bar, lalu angle
focus pada bagian tubuh tertentu – memaksimalkan long shot, short shot,
dan close-up secara proporsional – dia
merangkai jalinan deskripsi yang kuat bagi film-filmnya. Pertengahan menit ke-38, mulusnya long-take Brandon lari-lari menyusuri trotoar
dengan latar pemandangan etalase pertokoan, gedung-gedung perkantoran, dan jalanan
malam New York selama hampir empat menit yang digunakan pula pada promotional trailer-nya benar-benar suguhan
skill berkelas yang menunjukkan betapa
seriusnya McQueen memamerkan kebolehannya dalam berolah kamera. Dibalut
kemampuan menata tempo cerita yang tidak tergesa-gesa tapi juga tidak
berlambat-lambat, dengan tampilan visual jernih yang sungguh nyaman di mata
berkat fotografi mewah yang tajam, Shame mengangkat
subject matter yang kusut dan suram
tanpa terliat semuram, semenjijikkan, sejahat Irreversible (2002) Gaspar Noe yang gelap berputar-putar hingga menimbulkan
efek vertigo memualkan. Namun jangan teralihkan oleh prasangka anda sendiri, Shame berbeda dari The Reader (2008) meski sama-sama merujuk pada kisah kebejatan
moral manusia – sementara The Reader
menjadikan seks sebagai potongan kecil cinderamata untuk membongkar kembali
sebuah kuburan kenangan hidup yang pelik,
Shame tanpa sungkan-sungkan mengeksploitasi (peragaan) seks sebagai
hidangan utama ketimbang jualan lika-liku, sedu-sedan drama. Adegan-adegan koitus
yang frontal dan keberanian
Fassbender maupun Mulligan tampil tanpa busana memang cukup mengejutkan tapi
menurut hemat McQueen, agaknya itu “diperlukan” demi kepentingan naturalitas
cerita dan tercapainya target emotional
strike. Ditinjau dari segi bobot, intensitas, dan signifikansi, Shame mungkin tidak sebaik pendahulunya Hunger tapi secara full-frame, ini tetaplah karya yang memiliki kualitas yang tak bisa
diremehkan: sebuah visualisasi filosofi paradoks yang mengkonfrontasi fungsi
hormonal dalam manifestasi tubuh yang terjepit antara dorongan naluri manusiawi
dan kungkungan evaluasi jati diri yang mengedepankan kepantasan sekaligus membungkam
kehendak alam terbungkus dalam sebuah mantra ajaib terdiri dari tiga huruf yang
akan membuat kepala anda menoleh seketika mendengarnya: S.E.X.
-
F. Fajaryanto Suhardi
(8 Juni 2012)